Obrolan dengan salah seorang sahabat berujung pada pertanyaan ada apa dengan masyarakat yang saat ini kita tinggali? Keheranan kita bermula dari mengapa isu-isu picisan mudah naik ke permukaan, bahkan menjadi perdebatan di ranah publik.
Ada artis yang tak bisa masak mi instan atau tak bisa mengupas kulit salak direspons begitu riuh oleh masyarakat maya yang akrab disebut netizen atau warganet. Tapi respons berbeda ditunjukkan pada isu-isu yang mestinya menjadi perhatian bersama. Bukan hanya isu besar, tapi isu-isu kecil yang dampaknya signifikan bagi masyarakat.
Misalnya soal pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). Sudah menjadi rahasia umum kalau pembuatan KTP yang mestinya gratis tapi ada banyak oknum di level pemerintahan daerah menarik biaya pembuatannya.
Survei di lapangan, pembuatan KTP jika menggunakan calo berkisar antara Rp 100-150 ribu. Di salah satu kabupaten, biaya pembuatan KTP jika datang langsung ke kantor Dinas Pencatatan Sipil setempat Rp 50 ribu.
Sementara bagi mereka yang hendak mengurus sendiri akan diberi rintangan sedemikian rupa hingga prosesnya terkesan berbelit. Jurus andalan adalah dengan membuat lama proses pembuatan dengan dalih blangko KTP-nya habis.
Kalau sudah begini, prosesnya bisa tahunan. Bahkan ada cerita seseorang membuat KTP saat SMA dan baru jadi saat ia kerja setelah lulus kuliah.
Klaim blangko KTP habis memang masuk akal, tapi alasan habisnya saya kira karena mereka cenderung memprioritaskan masyarakat yang membayar untuk pembuatannya.
Belum lagi bagi mereka yang memang ingin membuat sendiri kartu identitasnya dihadapkan pada pungli hampir di tiap level pemerintahan. Ke RT, desa, sampai kecamatan pun mereka "ijo" akan duit.
Saya kerap mendengar alasan begini, "Kalau gak gitu (pungli) gaji kita kecil." Ini sebenarnya alasan klise dan saya yakin mereka pun tahu penyelesaiannya. Jika jadi abdi negara level bawah semestinya mereka paham akan konsekuensi bergaji kecil, dan mereka tak mungkin bisa kaya jika hanya mengandalkan gaji.
Makanya saya sering wanti-wanti ke orang-orang terdekat bahwa kalau mau kaya ya wirausaha bukan malah bertahan di pekerjaan yang bergaji kecil. Jika seperti ini akhirnya jadi "celamitan". Uang rakyat yang nominalnya tak seberapa akhirnya diembat juga.
Padahal kalau mereka mau "ngaji" rasa, mau ngaji di lingkungan mereka, rakyat itu buat nyari seperak, dua perak saja susahnya minta ampun. Jangan bandingkan dengan kondisi Anda yang orangtuanya sudah mapan secara finansial, tapi lihat pedagang-pedagang yang menjajakan jualannya di emperan jalan, mereka banting tulang untuk memasok penghidupan bagi keluarganya.
Ini baru satu isu, belum lagi isu soal pembuatan SIM yang harusnya rakyat tak mesti bayar banyak tapi di lapangan seakan kita membeli SIM. Mungkin ini juga sudah jadi rahasia umum bagi masyarakat kita.
Ini baru dua isu, ada juga isu mengenai pernikahan. Anda bisa bayangkan ijab kabul yang mestinya gratis (jika dilakukan di jam kerja), ditarik bayaran dengan nominal yang tak sedikit. Berkisar antara Rp 1,2 hingga 1,5 juta. Dan di masyarakat hal ini dianggap sebuah kewajaran. Masyarakat seperti apa yang menganggap wajar hal semacam ini dan riuh hanya karena ada artis tak bisa masak mi instan?
Memang bagi sebagian orang angka tersebut tak seberapa. Tapi bagi banyak orang saya yakin mereka keberatan kalau bukan karena terpaksa.
Lagi-lagi dalihnya karena gaji mereka kecil. Mereka yang melakukan ini tak lebih dari manusia bermental tempe tapi nafsu pengen kaya raya gede. Alhasil mereka tak mau ambil risiko untuk berwirausaha agar bisa kaya, malah celamit ke duit rakyat, kurang bedebah apa lagi coba?
Akhir coretan ini saya ingin ajak teman-teman ayo dong kita lebih peduli pada isu-isu yang memang signifikan bagi masyarakat. Dan tak acuhkan hal-hal receh yang tak ada signifikansinya bagi kehidupan kita. Bukankah sabda Rasul Muhammad SAW menyebut, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama?"
![The Grendeng Thinker [GRENTHINK] | Intellectual of Soedirman School](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG0S95wTNhM7inGW4n7pgOpD8YHNXXlnBE1rQFM4a_mrH3WpqLRqrDjqpKF9dCa9ZWIJEvqrXC_3Kouo9Xvnic8ZpEjKB9v61Kbfb4GPJ2AWgRnKEfF9ERQ46eMvJU5LgYHp9HWDtrcLN3/s1600/Grenthink+Logo.png)
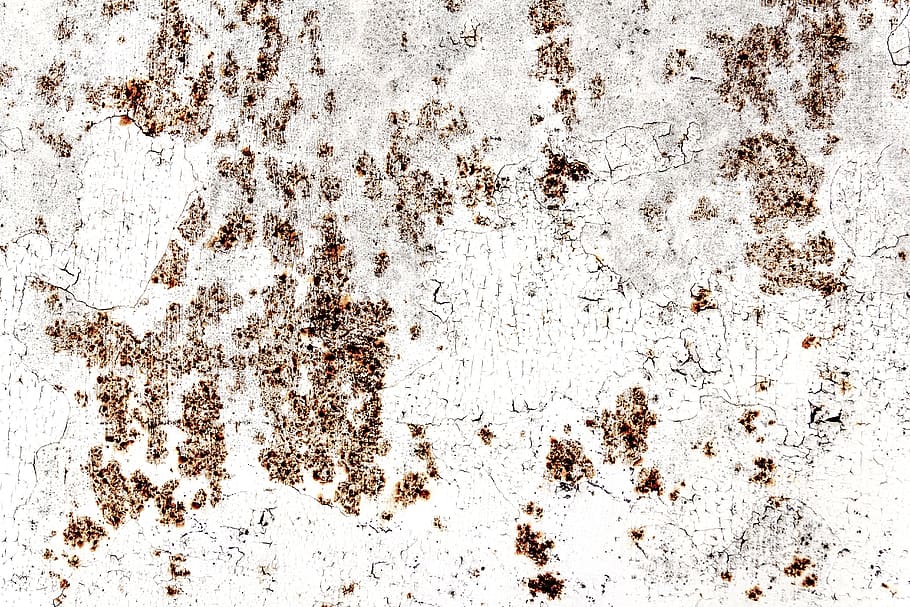
Tidak ada komentar:
Posting Komentar