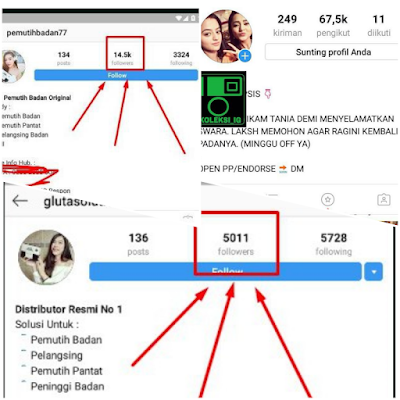Ilustrasi: Pixabay.com
Semasa SMA kami memperhatikan sejumlah forum di
internet yang sudah dalam kader “overdosis” untuk mendandani “ganja” sebagai
obat dari segala penyakit. Mantra itu
ternyata bukan hanya dipakai tukang obat pinggir jalan, tapi juga anak muda
yang belaga ilmiah.
Sebuah studi yang terbit dalam American Journal
of Health Promotion mengungkap, mereka yang kelewat proganja memiliki
pandangan berlebihan terhadap manfaat medis tanaman haram tersebut.
Studi yang bertajuk “Cannabis
Enthusiasts’ Knowledge of Medical Treatment Effectiveness and Increased Risks
From Cannabis Use” itu, berangkat dari survei terhadap pengunjung Ann Arbor
Hash Bash, yakni sebuah festival ganja tahunan di Amerika Serikat.
Studi yang dilakukan para peneliti dari
University of Buffalo, AS tersebut meminta sekitar 500 pengunjung acara untuk
menjawab kuis yang menguji wawasan mereka tentang ganja. Isi pertanyaan
berkutat mengenai dari mana mendapatkan informasi manfaat ganja, serta penyakit
apa saja yang bisa disembuhkan ganja.
Hasilnya mayoritas responden percaya bahwa
ganja dapat menyembuhkan epilepsi, depresi, bahkan sampai beberapa jenis
kanker. Namun anggapan para proganja ini ditentang National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) AS. NASEM menyebut pandangan itu
belum teruji secara ilmiah.
Mendandani ganja sebagai substansi yang penuh
dengan manfaat juga ramai ditulis media Tanah Air. Arahnya beraroma semangat
untuk membumikan ganja guna penggunaan medis. Layaknya cara kerja propaganda,
mereka selalu menjinjing citra “penderitaan” guna memantik empati di tengah
khalayak.
Kita masih ingat betul bagaimana
perjuangan Santi Warastuti, seorang ibu
asal Yogyakarta yang sempat menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan
penggunaan ganja demi keperluan medis. Upaya itu ditempuh lewat gugatan formal
ke MK untuk menghapus pasal larangan penggunaan narkotika golongan I. Ketentuan
itu termaktub dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) UU Narkotika.
Santi begitu ambisius membongkar ketentuan
dalam UU Narkotika tersebut demi pengobatan anaknya. Putri Santi bernama Pika,
menderita cerebral palsy, kelainan yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak,
dan koordinasi tubuh. Penggunaan terapi ganja disebut dapat meredakan gejala
kelainan yang dialami Pika.
Namun perjuangan Santi dipatahkan oleh putusan
MK yang kukuh untuk tidak mengizinkan penggunaan narkotika golongan-1, termasuk
ganja, meski untuk alasan medis.
Narasi khasiat ganja untuk pengobatan pasien
cerebral palsy terlacak dari studi para ilmuwan di Wolfson Medical Center,
Israel pada 2017 silam. Mereka mengklaim bahwa ganja medis secara signifikan
memperbaiki kondisi anak-anak yang menderita kelumpuhan otak atau cerebral
palsy.
Mereka menekankan bahwa berdasarkan “temuan
sementara” pengobatan dengan minyak ganja mengurangi gejala gangguan dan
meningkatkan keterampilan motorik anak-anak penderita cerebral palsy. Di
samping pula meningkatkan kualitas tidur, buang air besar, dan suasana hati
mereka secara umum.
Studi yang melibatkan 40 anak itu dilakukan
bersama perusahaan ganja medis Tikun Olam selama tiga tahun. Namun para peneliti menekankan, minyak ganja
tidak diharapkan untuk menggantikan obat lain yang dikonsumsi anak-anak
tersebut. Salah seorang peneliti di sana, Lihi Bar-Lev, menjelaskan bahwa
pengobatan ganja tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya pengobatan.
Salah seorang profesor Ikatan Dokter Indonesia
(IDI) sempat merespons mengenai isu legalisasi ganja medis ini. Prof. Dr. dr.
Zubairi Djoerban, Sp.PD, KHOM, yang juga Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Subspesialis Hematologi-Onkologi (Kanker) dari Pengurus Besar IDI pada Juni
lalu, pernah menyatakan bahwa belum ada bukti obat ganja lebih baik ketimbang
obat yang ada saat ini.
Termasuk untuk pengobatan nyeri kanker dan
epilepsi. Namun, menurut Prof. Zubairi
ganja medis bisa menjadi pilihan atau alternatif, tapi bukan yang terbaik.
Sebab, hingga detik ini belum ada penyakit yang ampuh ditangkal ganja.
Ketimbang menuntut legalisasi ganja medis,
Prof. Zubairi meminta Santi untuk bertemu dengan para ahli agar bisa menimbang
berbagai opsi pengobatan. Terlebih lagi, menurut Prof. Zubairi penggunaan ganja
bagi penderita cerebral palsy manfaatnya masih rendah.
Sebagai rakyat awam, saat itu kami memang
merasa sedikit janggal melihat seorang ibu memperjuangkan legalisasi ganja
medis. Mengingat temuan ilmiah manfaat ganja bagi pasien cerebral palsy masih
belum kukuh.
Dalam benak kami, ketika banyak opsi pengobatan
lain, mengapa yang dituntut malah legalisasi ganja medis. Jika pun pengobatan
itu terkendala pada “keuangan,” mengapa yang dituntut bukan hal yang memiliki
manfaat lebih luas. Misalnya kesehatan gratis bagi seluruh rakyat. Atau tidak
perlu muluk-muluk, mengapa tidak menuntut pengobatan penuh secara cuma-cuma
untuk Pika.
Kemasan cerita menyentuh dari seorang ibu yang
mempunyai anak dengan cerebral palsy, tentu membangkitkan empati publik. Ketika
ibu itu mengalasi perjuangannya untuk melegalisasi ganja medis dengan
penderitaan anaknya, maka sedikit banyak berhasil mengubah “citra” ganja. Ganja
belakangan lebih diasosiasikan sebagai obat ketimbang zat haram.
Padahal jika ditimbang secara adil, ganja juga
tidak sedikit mengandung mudarat. Seorang Ahli Saraf dari Stanford University School
of Medicine mengungkap bahwa pengguna ganja berpotensi empat kali lipat untuk
mengalami depresi berat secara kronis.
Profesor Neurobiologi dan Oftalmologi, Andrew
Huberman mengatakan bahwa ganja dapat meningkatkan kejadian depresi pada
individu yang tidak mengalami depresi sebelum mereka mulai mengonsumsi zat
haram tersebut.
Andrew Huberman menjelaskan bahwa ada data yang
menunjukkan kecemasan pengguna ganja kronis dapat meningkat dari waktu ke waktu
jika mereka melanjutkan kebiasaannya. Kecemasan juga bisa terjadi saat pengguna
tengah dalam kondisi mabuk karena efek ganja.
Hal ini terjadi lantaran reseptor CB1 pada
tubuh manusia, yang berperan mengikat THC (bahan aktif dalam ganja yang membuat
mabuk) ketika masuk ke dalam tubuh mengalami keausan. Seiring waktu, ada lebih
sedikit reseptor yang tersedia dan pensinyalan yang berada di hilir reseptor
tersebut menjadi semakin tidak kuat atau melemah.
Sehingga membuat seseorang membutuhkan lebih
banyak “ganja” untuk berada dalam tahap seperti kali pertama menghisap ganja.
Dan pola ini bakal meningkat secara terus menerus.
Promosi akan khasiat ganja kami rasa sudah
dalam tahapan overdosis. Sejumlah pihak seakan menanggalkan Sains demi
mendorong legalisasi ganja medis.
Kami sepakat bahwa diskursus mengenai ganja harus
diletakan pada meja saintis, bukan publik. Sebab merekalah yang mampu dan
mempunyai timbangan untuk membedah masalah ini.
Jika dilempar ke tengah publik, maka yang
muncul narasi-narasi propagandis. Seperti diungkap Anthony Pratkanis dalam The
Age of Propaganda, propaganda mengacaukan pesan utama untuk menyebarkan
informasi tanpa dipahami orang.
Propaganda tidak seperti persuasi yang
bermaksud agar targetnya memiliki kesempatan yang adil untuk menilai.
Sebaliknya, ini beroperasi dengan membuat individu lengah dan memengaruhi
mereka tanpa sepengetahuannya.
Untuk melakukan ini, propagandis
mempresentasikan ide mereka dalam kemasan yang menarik secara visual,
mengalihkan target dari fokus pada apa yang sebenarnya disampaikan. Hal ini
dilakukan dengan penggunaan bahasa yang positif dan penataan informasi dengan
cara yang menarik untuk mengalihkan perhatian target dari kebenaran asertif.
Makanya mereka yang proganja kerap membalut
legalisasi ganja medis dengan kisah-kisah menyentuh hati. Tanpa membahasa lebih
jauh dampak penggunaan jangka panjang zat itu; atau alternatif obat lain yang
sudah teruji secara klinis.
Lebih jauh lagi, kalau memang mereka serius
prokesehatan publik, maka mereka bisa mengarahkan opini publik untuk menuntut
bahwa kesehatan merupakan hak seluruh individu dan negara mesti memfasilitasi
itu dengan menggratiskan biaya pengobatan. Bukan malah ujug-ujug meminta
legalisasi ganja.
Referensi
Andrew Huberman.The Effects of Cannabis (Marijuana) on the Brain & Body. YouTube, 2022. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=gXvuJu1kt48.
Anthony Pratkanis dan Elliot Aronson. The Age
of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion. Henry Holt and
Company, 2001
Daniel J. Kruger, PhD, dkk. Cannabis
Enthusiasts’ Knowledge of Medical Treatment Effectiveness and Increased Risks
From Cannabis Use. American Journal of Health Promotion, 2020.
Ido Efrati. Medical Marijuana Helps Kids With
Cerebral Palsy, Israeli Study Finds. Haaretz, 2017. Diakses melalui
https://www.haaretz.com/israel-news/2017-09-07/ty-article/.premium/medical-marijuana-helps-kids-with-cerebral-palsy-study-finds/0000017f-db4b-db22-a17f-fffb28600000.
![The Grendeng Thinker [GRENTHINK] | Intellectual of Soedirman School](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG0S95wTNhM7inGW4n7pgOpD8YHNXXlnBE1rQFM4a_mrH3WpqLRqrDjqpKF9dCa9ZWIJEvqrXC_3Kouo9Xvnic8ZpEjKB9v61Kbfb4GPJ2AWgRnKEfF9ERQ46eMvJU5LgYHp9HWDtrcLN3/s1600/Grenthink+Logo.png)