Ilustrasi: Pixabay.com
Topik Kunci:
- Indonesia ikut menolak rencana pembahasan mengenai situasi HAM yang menimpa muslim Uyghur di China dalam Dewan HAM PBB.
- Pengaruh China di Indonesia.
- Laporan Dewan HAM PBB mengenai dugaan terjadinya kejahatan internasional terhadap muslim Uyghur, seperti kekerasan seksual, penyiksaan, serta penahanan dan sejumlah tindak kekerasan lainnya.
- Dugaan pemerkosaan di dalam kamp.
Kalimat Kunci:
Program deradikalisasi dan pendidikan ulang muslim Uyghur di wilayah Xinjiang mendapat sorotan Barat. Program yang dilakukan di sebuah tempat itu, lebih menunjukkan kamp konsentrasi ketimbang tempat belajar. Dewan HAM PBB melaporkan bahwa terjadi sejumlah dugaan pemerkosaan bahkan sebagian penghuni mengaku dipaksa melakukan oral seks oleh panjaga.
Penolakan Indonesia terhadap proposal pembahasan mengenai dugaan pelanggaran HAM terhadap muslim Uyghur di Xinjiang, China dalam Dewan HAM PBB, cukup mengecewakan. Indonesia bersama negara muslim lain, Pakistan berdiri di barisan 19 negara untuk menentang pembahasan mengenai laporan penindasan terhadap etnis Uyghur pada Kamis pekan lalu.
Kementerian Luar Negeri berdalih, penolakan tersebut lantaran mereka menimbang pembasahan tersebut tidak akan menghasilkan kemajuan berarti untuk menuntaskan dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis muslim China itu. Mengingat China dan sejumlah negara lain yang berkepentingan menolak pembahasan tersebut.
Perwakilan permanen Indonesia di Jenewa, Swiss, Febrian A Ruddyard memastikan, penolakan terhadap pembahasan mengenai situasi HAM di Xinjiang tidak menggugurkan komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM. Indonesia diakui Febrian masih kukuh untuk turut mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia termasuk di Xinjiang.
Propaganda Barat menjadi ramuan ampuh bagi sebagian pihak yang pro-Beijing untuk membius masyarakat Indonesia akan situasi HAM di Xinjiang. Narasi dikonstruksi sedemikian rupa agar melanggengkan anggapan bahwa yang dilakukan China sebagai upaya menumpas ekstremisme agama. Organisasi nirlaba yang berpusat di Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), Freedom House mengidentifikasi besarnya pengaruh media Beijing terhadap perdebatan mengenai isu Uyghur dalam ruang publik Tanah Air.
Pengaruh China merembet ke Kantor Berita Antara serta stasiun TV swasta. Hal itu dilakukan dalam sebuah kerangka kerja sama guna memastikan liputan positif terhadap China pada pemberitaan nasional.
Periode 2019-2020, sejumlah jurnalis dan influencer media sosial telah diundang dalam perjalanan bersubsidi di seluruh China. Pascaperjalanan tersebut para peserta seakan merepetisi narasi yang dikumandangkan China mengenai situasi yang dialami oleh komunitas Uyghur. Termasuk penyangkalan atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
Pemerintah China juga telah menyubsidi perjalanan singkat ke China serta program pendidikan jangka panjang untuk pelajar dan pemimpin dari ormas Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Sekembalinya dari sana, beberapa peserta membingkai kebijakan pemerintah China di wilayah tersebut secara positif, sementara yang lain menegaskan sikap kritis.
Freedom House menyebut, sebagian besar dari mereka yang menyetujui kebijakan Pemerintah China adalah mahasiswa Indonesia di universitas-universitas China, banyak dari mereka telah mempublikasikan refleksi mereka pada media arus utama untuk menulis propaganda pro-Beijing.
Beijing juga mencoba untuk menyasar kalangan pimpinan umat Islam Tanah Air. Pada Februari 2019 silam, China mengundang tiga jurnalis bersama lima belas perwakilan dari delegasi Ormas Islam Indonesia untuk mengintip kondisi Xinjiang. Agung Danarto, seorang sekretaris senior Muhammadiyah dan ulama yang melakukan tur Februari, memandang positif kamp tempat minoritas muslim di China itu.
“Tempat, kamp, asrama dan ruang kelas [di Xinjiang] sangat nyaman dan layak, dan tidak terlihat seperti penjara,” ucap Agung mengutip majalah resmi Muhammadiyah.
Pernyataan Agung diterbitkan setelah Muhammadiyah mengeluarkan pandangan mengenai isu Uyghur pada Desember 2018 yang mengkritik tindakan pemerintah China di Xinjiang. Dua peserta perjalanan dari Nahdlatul Ulama (NU), yakni Wakil Sekjen Masduki Baidlawi dan Wakil Ketua Robikin Emhas seakan mengulangi pernyataan Beijing bahwa Uyghur diberikan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah ekstremisme. Meskipun mereka juga mengakui bahwa penghuni kamp tidak memiliki tempat untuk salat serta tidak tersedianya makanan halal. Sikap NU terhadap kebijakan Beijing di Xinjiang dianggap ambivalen.
Peserta tur lain yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, KH Muhyiddin Junaidi mencatat bahwa kunjungan tersebut dikontrol dengan ketat. Di sana dia juga melihat bahwa orang-orang Uyghur yang dia temui tampak takut untuk mengekspresikan diri secara jujur. Junaidi juga mengkritik Kementerian Luar Negeri Indonesia karena diam terhadap kebijakan Uyghur China.
Situasi yang menimpa komunitas muslim Uyghur getol didengungkan negara-negara Barat yang diametral secara ideologis dengan China. Sejumlah pihak menengarai desakan Barat atas situasi HAM di Xinjiang murni dimotori kepentingan anti-China. Setidaknya demikian yang digembar-gemborkan kalangan pro-Beijing di Indonesia.
Terlepas dari itu, sulit membayangkan ketika seseorang ditahan bukan karena aksi kejahatan, melainkan hanya karena dia melakukan perjalanan ke luar negeri atau memberikan donasi.
Hal demikianlah yang dialami muslim Uyghur di China. Laporan Dewa HAM PBB pada 31 Agustus 2022, menyebut bahwa seorang muslim Uyghur dapat ditempatkan dalam kamp cuci otak Beijing hanya karena melakukan salah satu atau kedua hal tersebut.
Kamp cuci otak yang dinamai sebagai Vocational Education and Training Centres (VETC) itu diklaim Beijing sebagai wadah untuk memberikan pelatihan teknis bagai muslim Uyghur di Xinjiang. China berkali-kali menegaskan bahwa di dalam sana mereka begitu menghargai hak para peserta.
Kamp yang bagi China ditujukan untuk deradikalisasi serta pendidikan ulang itu tak ubahnya seperti tahanan. Temuan Dewa HAM PBB menunjukkan bahwa dua pertiga dari 26 mantan tahanan yang diwawancarai, dilaporkan telah menjadi sasaran penyiksaan. Penyiksaan bahkan dialami oleh sebagai orang sebelum mereka ditempatkan dalam kamp tersebut.
Menurut laporan tersebut, penganiayaan ini terjadi selama interogasi atau sebagai bentuk hukuman atas (dugaan) kesalahan mereka yang belum tentu terbukti. Mereka mengaku dipukuli dengan tongkat, termasuk tongkat listrik sambil diikat di apa yang disebut “kursi harimau.”
Bukan hanya itu, mereka juga menjadi sasaran interogasi dengan air dituangkan ke wajah mereka, serta kurungan isolasi yang berkepanjangan, dan dipaksa untuk duduk tak bergerak di bangku kecil untuk waktu yang lama. Orang yang melaporkan bahwa dirinya dipukuli untuk sebuah pengakuan pelanggaran yang tidak dilakukan dirinya, digambarkan dibawa ke ruang interogasi yang terpisah dari sel atau ruang asrama tempat orang tinggal. Lebih dari dua pertiga individu juga melaporkan bahwa, sebelum dipindahkan ke fasilitas VETC, mereka ditahan di kantor polisi, di sana mereka menggambarkan kejadian serupa dipukuli serta dilumpuhkan di “kursi harimau.”
Dewan HAM PBB juga mendapat pengakuan dari sejumlah mantan tahanan di sana yang sempat dibelenggu saat menjalani sebagian masa tahanan. Lebih mengerikan lagi, mereka di sana juga mengalami kelaparan secara terus menerus yang berujung pada penurunan drastis berat badan.
Penderitaan ini belum berakhir, mereka juga dilarang untuk tidur nyenyak karena lampu di dalam tempat mereka tidak dimatikan sehingga membuat para tahanan kesulitan untuk tidur.
Beberapa juga mencatat bahwa mereka tidak diizinkan untuk berbicara dalam bahasa mereka sendiri (baik Uyghur atau Kazakh) dan tidak dapat menjalankan agama mereka, seperti salat. Satu orang yang diwawancarai menggambarkan pengalaman mereka sebagai berikut:
“Kami dipaksa menyanyikan lagu patriotik demi lagu patriotik setiap hari, sekeras mungkin dan sampai sakit, sampai wajah kami menjadi merah dan urat kami muncul di wajah kami.”
Laporan Dewan HAM PBB juga menyebut adanya sejumlah bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Mereka dipaksa oleh penjaga kamp untuk melakukan oral seks saat proses interogasi.
Mereka juga dipaksa untuk menanggalkan busananya sehingga dalam keadaan telanjang. Sumber Dewan HAM PBB mengatakan, penghuni kamp tersebut mengalami pemerkosaan di sejumlah titik, seperti terjadi di luar asrama, di kamar terpisah yang tak terpantau kamera pengawas.
Mementahkan apa yang dilaporkan Dewan HAM PBB itu dengan tudingan “propaganda Barat,” sama seperti segolongan pro-Soeharto yang mengatakan bahwa rezim Soeharto tanpa dosa. Terlepas dari isu ini ditunggangi Barat atau Timur, Kanan atau Kiri, Konservatif atau Liberal, aksi nyata Indonesia amat dibutuhkan. Bukan hanya berlindung pada slogan “kami menghargai HAM” tapi nir-langkah nyata.
Terdapat dua negara dengan penduduk muslim terbesar yang turut memblok upaya Barat untuk membawa isu Uyghur ke Dewan HAM PBB, yakni Indonesia dan Pakistan. Langkah ini dicap Human Rights Watch sebagai kemunafikan. Sebab keduanya merupakan anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), di mana organ itu melihat selama ini OKI mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pelanggaran HAM yang menimpa komunitas muslim lainnya, seperti etnis Rohingya di Myanmar dan apartheid yang dilakukan oleh otoritas Israel di Palestina. Namun, ketika sampai pada pelanggaran yang dihadapi oleh Uyghur dan muslim Turki lainnya di China, keduanya membisu.
Laporan lengkap Dewan HAM PBB: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
![The Grendeng Thinker [GRENTHINK] | Intellectual of Soedirman School](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG0S95wTNhM7inGW4n7pgOpD8YHNXXlnBE1rQFM4a_mrH3WpqLRqrDjqpKF9dCa9ZWIJEvqrXC_3Kouo9Xvnic8ZpEjKB9v61Kbfb4GPJ2AWgRnKEfF9ERQ46eMvJU5LgYHp9HWDtrcLN3/s1600/Grenthink+Logo.png)

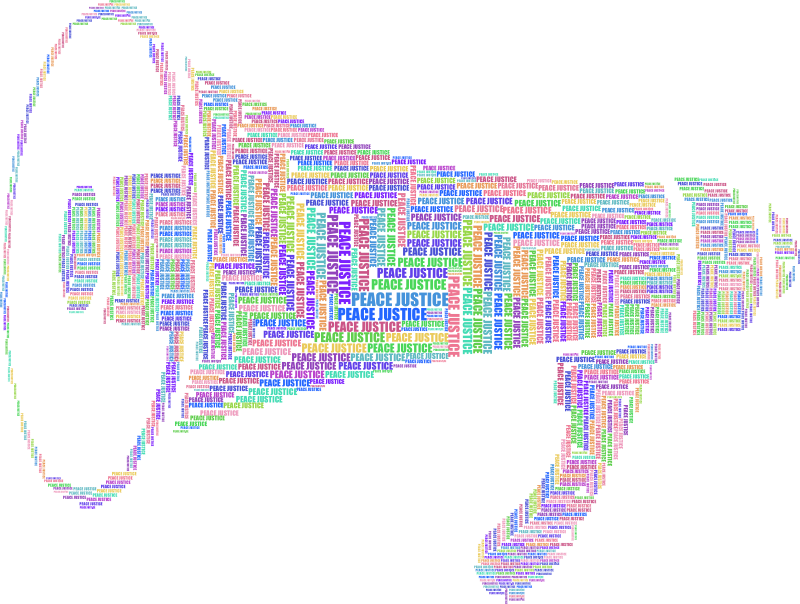


.jpg)






